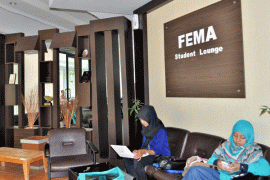Jakarta (ANTARA) - Fenomena #KaburAjaDulu sempat menjadi perbincangan ramai di media sosial, terutama oleh generasi muda yang mengaku lelah menghadapi kondisi politik, ekonomi, serta sosial yang tak menentu.
Di tengah situasi yang "tak menentu" itu, mereka ramai-ramai menggemakan gerakan kabur ke luar negeri untuk mendapatkan peruntungan lebih baik dari segi pekerjaan maupun pendidikan.
Salah satu dampak yang menjadi kekhawatiran dengan ramainya tagar ini adalah brain drain, yakni keluarnya tenaga kerja berkualitas yang terdidik ke luar negeri sehingga tenaga di dalam negeri menjadi berkurang.
Namun, terlepas dari kekhawatiran-kekhawatiran khalayak akan berkurangnya tenaga berkualitas di Indonesia, fenomena tersebut justru ditanggapi secara positif oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Amich Alhumami.
Menurut dia, brain drain kini memiliki pemaknaan baru. Jika dulu brain drain disesali karena orang-orang terbaik pergi meninggalkan Indonesia, kini brain drain justru dapat dipahami dalam perspektif baru yang lebih bisa mendatangkan keuntungan berlipat ganda bagi negara yang mengalaminya.
“Jadi orang-orang pintar Indonesia pergi ke luar negeri, memperoleh kesempatan sekolah dan kemudian bekerja di sana. Nah, dengan bekerja di sana, mereka bisa menambah pengetahuan dan pengalaman. Kita bisa bayangkan bahwa orang-orang terbaik bisa bekerja di Yahoo, Google, atau perusahaan multinasional di sektor-sektor yang strategis, dan pada waktunya jika mereka kembali ke Indonesia, maka yang diperoleh bukan lagi brain drain melainkan brain gain,” katanya.
Negara-negara maju seperti Korea dan China, menurut dia, telah menerapkan hal tersebut dan kini memiliki talenta-talenta terbaik yang menjadi representasi kedua negara maju itu di mata dunia. Jika hal yang sama dilakukan melalui strategi yang benar oleh Pemerintah Indonesia, maka di masa depan, Indonesia juga akan menyusul menjadi negara maju yang mampu memanfaatkan talenta-talenta terbaiknya untuk berkontribusi bagi kemajuan negara.
Saat ini, berdasarkan data agregat, Malaysia menempati urutan tertinggi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) terbanyak, sebanyak 2.540.450. Mayoritas dari mereka adalah pekerja migran di sektor perkebunan, konstruksi, serta asisten rumah tangga. Selain itu, terdapat pula WNI yang menikah dengan warga setempat yang generasi keturunannya masih mempertahankan kewarganegaraan Indonesia.
Di urutan kedua adalah Arab Saudi, dengan total 857.613 WNI, yang mayoritas bekerja di sektor domestik dan pelayanan haji serta umrah. Kota-kota seperti Riyadh, Jeddah, dan Makkah menjadi pusat populasi WNI di negara ini.
Urutan ketiga ditempati Taiwan, dengan total 238.639 WNI. Taiwan menjadi destinasi utama pekerja migran asal Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan tenaga kerja domestik. Selain itu, cukup banyak mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di berbagai universitas di Taiwan.
Menurut Amich, apabila ada 1 atau 2 persen pemuda yang diberikan kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri dan nantinya memiliki pengalaman 1 atau 2 tahun bekerja di sana, maka ketika kembali ke Indonesia, mereka harus mendapatkan jaminan pekerjaan atau tempat untuk berkarya dengan pendapatan yang sepadan, serta pengaman sosial yang lebih baik.
“Diharapkan ketika kembali lagi, itu harus disiapkan. Kalau misalnya mereka sebagai peneliti, dosen, maka kita harus membangun perguruan tinggi yang bagus dengan pengembangan bidang-bidang keilmuan yang relevan, dan itu dikaitkan dengan strategi pengembangan kewilayahan,” ujar dia
Pemetaan potensi kewilayahan juga menjadi salah satu hal penting apabila ingin menuai brain gain di Indonesia; sehingga perlu mengidentifikasi sektor-sektor strategis atau bidang-bidang ilmu apa yang harus ditawarkan dan dikembangkan.
"Misalnya di daerah Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Sarawak (pintu masuk ke Malaysia), yang memiliki potensi ekonomi maritim., atau di daerah-daerah lain, yang memiliki potensi ekonomi pertanian untuk dikembangkan," kata Amich.
Belajar dari negara-negara lain
Amich mencontohkan pengalaman dari Ethiopia, Afrika Timur, yang pernah menjadi negara sangat miskin dengan pendapatan per kapita sekitar 100-300 dollar saja. Akibat minimnya lapangan pekerjaan, maka secara otomatis juga menyebabkan perekonomian tidak tumbuh, ditambah dengan konflik sosial politik yang tidak teratasi.
“Mereka pergi ke luar Jadi lebih mudah menemukan insinyur atau dokter orang Ethiopia di Chicago, di Boston, atau di California (Amerika Serikat) daripada di Addis Ababa (Ibukota Ethiopia), tetapi, setelah pembangunan dimulai, konflik sosial-politik diatasi, lalu strategi domestiknya itu adalah dengan membangun institusi perguruan tinggi, sekolah-sekolah yang bagus, lalu lapangan pekerjaan tersedia karena investasi mulai masuk,” paparnya.
Ia menjelaskan, orang-orang terbaik yang semula bekerja di luar negeri, secara otomatis kembali ke Ethiopia sehingga kini perkembangan di Ethiopia itu perlahan maju, dari semula mengalami brain drain, menjadi berhasil memetik brain gain.
Untuk itu, ia menyarankan agar investasi pemerintah di Indonesia difokuskan pada pembangunan perguruan tinggi untuk mengembangkan riset-riset inovatif yang dapat mendukung pembangunan ekonomi kewilayahan.
Selain belajar dari Ethiopia, Pemerintah Republik Indonesia juga bisa belajar dari Singapura, yang berhasil mendatangkan salah satu musisi ternama, Taylor Swift, pada tahun 2024 yang lalu. Tak tanggung-tanggung, selama enam hari berturut-turut, pelantun lagu “Love Story” tersebut tampil di Negeri Singa tersebut.
Keberhasilan tersebut dinilai sebagai sebuah kesuksesan memanfaatkan globalisasi, yang dilakukan melalui beberapa strategi, di antaranya menciptakan lingkungan bisnis yang kuat dengan kemudahan-kemudahan izin berbisnis, sistem pajak yang rendah, meningkatkan hibah dan inisiatif dari pemerintah, serta mengumpulkan tenaga kerja yang berkualitas.
Selain itu, China misalnya, juga memiliki Program Ribuan Bakat (Thousand Talents Program/TTP) yang diluncurkan pada 2008 untuk menarik ilmuwan, insinyur, dan pengusaha terkemuka China dari luar negeri (terutama dari AS dan Eropa). Melalui TTP, China menawarkan gaji yang tinggi, hibah penelitian, dan tunjangan perumahan untuk membujuk para profesional China kembali.
Sedangkan Korea, negara yang berhasil menciptakan pasar Korean Pop (K-Pop) yang membuktikan keberhasilan diplomasi budayanya, juga memiliki inisiatif dalam mengatasi brain drain, yakni dengan membangun Institut Sains dan Teknologi Korea (KIST), sebuah lembaga riset nasional pertama di Korea Selatan, yang didirikan dengan dukungan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada keahlian pihak asing.
"Rumput tetangga"
“Rumput tetangga memang terlihat lebih hijau,” demikian pepatah yang rasanya masih begitu relevan dari waktu ke waktu.
Hal itu setidaknya tercermin dari lini media sosial yang sempat didominasi oleh tagar #KaburAjaDulu, yang mendorong generasi produktif untuk merantau ke luar negeri.
Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa tagar yang menjadi trending secara organik seperti “Kabur Aja Dulu” merupakan sebuah cara bagi generasi muda mengekspresikan pendapat mereka terkait masa kini dan masa depan mereka di negeri sendiri.
Ini merupakan fenomena yang menarik, karena kecemasan itu hadir ketika Indonesia tengah memiliki bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia nonproduktif.
Berdasarkan data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada Februari 2024, jumlah penduduk usia kerja telah meningkat dari yang sebelumnya berjumlah 206,71 juta orang pada Agustus 2021, menjadi 212,59 juta pada Agustus 2023.
Dari penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 69,48 persen (147,71 juta orang atau setara dengan 52,87 persen dari total penduduk) merupakan angkatan kerja, di mana 5,32 persen (7,86 juta orang) di antaranya tergolong ke dalam kategori pengangguran terbuka.
Jumlah penduduk usia produktif idealnya mampu menghadirkan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi serta menyongsong “Indonesia Emas 2045”.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa mereka dapat berkontribusi jika ada dukungan dari pihak-pihak terkait, khususnya dalam hal ketenagakerjaan.
Dua diaspora Indonesia di Australia, Fierza dan Dana, menilai #KaburAjaDulu bukan hanya sekadar tren “iseng”, tapi juga suara utamanya terkait peluang kerja dan pemenuhan hak pekerja Indonesia yang lebih baik.
Mereka mencontohkan bagaimana periode “honeymoon” perusahaan-perusahaan rintisan (start-up) yang begitu menyegarkan bagi skena industri dan inovasi teknologi beberapa waktu lalu, kini sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Pun dengan ketidakpastian para pekerja yang mengembangkan perusahaan-perusahaan tersebut.
“SDM kita tuh sebenarnya berbakat banget. Tapi kalau tidak diberikan perhatian oleh pemerintah, jangan heran kalau banyak yang akhirnya memilih untuk mencari kesempatan di luar negeri,” kata Dana.
“Alarm”
Cuitan-cuitan di tagar “Kabur Aja Dulu” cukup didominasi dengan kekhawatiran soal ketenagakerjaan yang menantang dari kacamata anak-anak muda — sang penghuni bonus demografi Indonesia.
Banyak dari mereka menyoroti sulitnya mendapatkan pekerjaan yang laik, gaji dan apresiasi yang sepadan, persyaratan rekrutmen kerja yang lebih inklusif, hingga kepastian untuk bisa hidup dengan settle di masa mendatang.
Tidak berlebihan rasanya jika menyebut #KaburAjaDulu sebagai sebuah “alarm” daripada hanya sekadar menganggapnya sebagai “omong-omong kosong” belaka dari para generasi penerus bangsa.
Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai, diksi “kabur” pada tagar tersebut memang mengindikasikan wujud kritik sosial, yang di era masyarakat digital ini, sangat memungkinkan publik untuk mengekspresikan gagasan dan sikapnya.
Ida mengatakan, kekuatan media sosial dalam menggerakkan massa tidak bisa dipungkiri, termasuk menggerakkan anak muda. Bahkan, ada istilah ‘the power of netizens’ yang menunjukkan besarnya peran media sosial dalam berbagai aktivisme digital.
Namun, di tengah kecemasan terkait kondisi di Ibu Pertiwi itu, mereka yang menggunakan tagar ini juga memanfaatkannya untuk berbagi informasi soal beasiswa, lowongan kerja, hingga pengalaman bekerja di negara-negara lain.
Ada semangat untuk saling membantu satu sama lain, yang rasanya seperti setitik cahaya di tengah kegelapan.
Febrian, diaspora Indonesia yang telah menetap dan bekerja di Belanda selama tujuh tahun, mengatakan bahwa memerlukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan besar ini.
Sementara bagi Rahma yang kini bekerja dan tinggal di Jepang, hal penting lainnya sebelum memutuskan untuk merantau ke negeri orang adalah kesiapan bekal kemampuan diri, mulai dari bahasa hingga keahlian.
“Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah sudah menyiapkan hal-hal ini sebelum memutuskan merantau ke negara lain, mulai dari bahasa asing, modal atau biaya, mental, jauh dari keluarga, serta penyesuaian gaya hidup dan budaya baru,” ujar Rahma.
Refleksi
Di tengah segala gejolak yang terjadi belakangan ini, #KaburAjaDulu juga dapat dilihat sebagai sebuah refleksi bagi pemerintah — regulator yang memiliki peran vital khususnya dalam ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai isu yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Yassierli juga menilai tagar #KaburAjaDulu menjadi perhatian dan catatan khusus bagi pemerintah. “Ini tantangan buat kami kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo, pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” kata Menaker pada Senin (17/2).
Yassierli juga menilai tagar #KaburAjaDulu bukan berarti ajakan untuk kabur, melainkan keinginan untuk meningkatkan kompetensi (skill) dan mendapatkan peluang bekerja yang lebih baik di luar negeri, dan bisa kembali untuk membangun Ibu Pertiwi.
Sementara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan #KaburAjaDulu menjadi momen bagi pemerintah untuk meresponsnya menjadi suatu masukan.
Jika ditelaah lebih jauh, #KaburAjaDulu rasanya bukanlah sebuah ajang untuk saling menakuti, pun untuk mempertanyakan nasionalisme mereka yang mencari kesempatan di negara lain.
Toh, mencintai Indonesia bukan sebuah kompetisi, karena rasa cinta itu tetap ada melalui kepedulian, melalui sebuah sikap — walaupun raganya tidak sedang berada di Tanah Air.
Namun, alangkah indahnya jika rasa cinta bangsa ini terbalas juga oleh negara.
Keseimbangan antara masyarakat yang proaktif menyuarakan aspirasinya, diperlukan bersama dengan pemerintah yang mau mendengar dan terbuka akan hal tersebut.
Dengan itu, asa untuk mendapatkan kesejahteraan yang laik oleh negara tentu akan tumbuh bersama dengan peluang menuju cita-cita pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, dan pada akhirnya mencapai Indonesia Emas dua dekade mendatang.
Baca juga: Kadin Bogor ajak pengusaha tanggapi positif tagar #KaburAjaDulu
Baca juga: Menkomdigi: #KaburAjaDulu bentuk kebebasan berekspresi
Baca juga: Berbagai respons pemangku kepentingan tanggapi tren #KaburAjaDulu